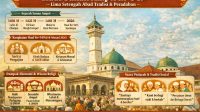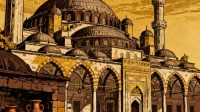SURABAYA, headlinejatim.com – Di tengah riuhnya perayaan hari-hari besar nasional, ada satu tanggal yang sering luput dari perhatian publik. Ia hadir tanpa gegap gempita, namun menyimpan makna paling mendasar bagi keberlangsungan hidup: 10 Juli, Hari Krida Pertanian.
Ditetapkan lewat Keputusan Presiden Nomor 247 Tahun 1963, Hari Krida Pertanian ditujukan untuk memberi penghormatan kepada para petani, peternak, dan nelayan. Mereka yang tak pernah tampil di panggung, tapi menjadi fondasi pangan negeri ini.
Tanggal 10 Juli dipilih bukan tanpa alasan. Dalam sistem kalender agraris Jawa kuno bernama Pranata Mangsa, hari ini menandai dimulainya musim tanam kedua, ketika tanah mulai siap kembali menerima benih dan harapan baru ditanamkan.
Namun ironisnya, di era modern ini, peringatan Hari Krida Pertanian justru makin sepi. Padahal, dari ladang-ladang itulah kehidupan kita dimulai.
Negeri Agraris yang Terancam Krisis Petani
Meski Indonesia dikenal sebagai negara agraris, kenyataan di lapangan justru mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 28 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor pertanian. Namun yang mengkhawatirkan, mayoritas dari mereka berusia di atas 45 tahun.
Generasi muda mulai menjauhi sawah. Citra pertanian yang dianggap kotor, berat, dan tidak menguntungkan membuat anak-anak petani enggan meneruskan jejak orang tuanya. Padahal, jika tak segera ada regenerasi, siapa yang akan menanam padi, memanen jagung, atau menyemai cabai di masa depan?
Sementara itu, alih fungsi lahan terus berjalan. Kementerian ATR/BPN mencatat, Indonesia kehilangan rata-rata 96 ribu hektare lahan pertanian produktif setiap tahun, yang sebagian besar berubah menjadi permukiman dan kawasan industri.
Tak heran jika Indonesia masih harus mengimpor lebih dari 3 juta ton beras pada 2023, meski memiliki tanah subur dan varietas padi lokal yang kaya.
Budaya Bertani, Warisan yang Mulai Ditinggalkan
Bagi masyarakat Indonesia, bertani bukan hanya soal ekonomi. Ini adalah bagian dari budaya dan spiritualitas. Di berbagai daerah, masih hidup tradisi seperti Sedekah Bumi di Jawa, Mapag Sri di Sunda, dan Subak di Bali. Semua menjadi bukti bahwa tanah, air, dan hasil panen dipandang sebagai anugerah yang harus dihormati.
Sayangnya, modernisasi yang tak berpijak pada akar budaya justru membuat warisan itu luntur. Kuliner tradisional berbasis hasil tani seperti tiwul, gatot, gembili, jagung titi, dan papeda perlahan menghilang dari meja makan generasi muda. Makanan-makanan ini dulunya adalah simbol ketangguhan dan kearifan lokal dalam menghadapi masa sulit. Kini, tergeser oleh makanan instan dan selera global.
Benih Harapan: Ketika Anak Muda Kembali ke Desa

Meski situasi terlihat suram, masih ada cahaya di ujung sawah. Di berbagai daerah, muncul gerakan anak muda yang kembali ke desa. Di Kulonprogo, Sleman, Jember, hingga Tabanan, komunitas petani muda mulai mengembangkan pertanian organik, sistem pertanian cerdas berbasis teknologi, hingga model ekowisata agro.
Di kota-kota besar, gerakan urban farming menjamur. Lahan-lahan sempit disulap jadi kebun vertikal, hidroponik, bahkan peternakan mini. Semua ini menunjukkan bahwa pertanian bisa tampil modern, berkelas, dan tetap berpijak pada nilai lokal.
Mereka tak hanya menanam sayur. Mereka sedang menanam harapan. Bahwa pangan bisa diproduksi secara adil, lestari, dan bermartabat.
Peringatan yang Seharusnya Menggetarkan
Hari Krida Pertanian seharusnya menjadi pengingat nasional, bahwa bangsa ini berdiri bukan di atas gedung pencakar langit, tetapi di atas ladang dan sawah yang dijaga dengan susah payah. Kita bisa hidup tanpa ponsel, tapi tidak tanpa pangan. Kita bisa tunda belanja, tapi tidak bisa tunda makan.
Petani bukan objek belas kasihan. Mereka adalah pelaku utama peradaban. Tugas kita bukan hanya mengapresiasi, tapi juga melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, memperbaiki sistem distribusi pangan, dan memastikan harga jual yang layak.
Menoleh ke Akar, Menyemai Masa Depan
Pada 10 Juli ini, mari menoleh ke belakang. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk menyadari bahwa masa depan harus ditanam hari ini. Di tanah yang benar, dengan niat yang jernih.
Karena saat kita makan nasi hari ini, ada peluh petani yang tak pernah kita lihat. Saat kita menikmati sayur dan buah segar, ada tangan-tangan lelah yang bekerja sejak fajar. Kita tak perlu jadi petani untuk menghargai mereka. Kita hanya perlu peduli, dan tak lagi memalingkan wajah.
Hari Krida Pertanian bukan hari seremonial. Ia adalah hari spiritual. Saat kita diingatkan kembali: siapa yang benar-benar memberi kita makan.