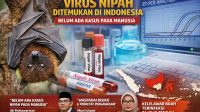Oleh: Bunga Agrima Riskika Sari*

Secara geografis, Indonesia terletak di daerah tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Hal ini membuat negeri kepulauan ini sebagai salah satu daerah yang memiliki hujan tropis tertinggi dengan air melimpah.
Setting geologi dan kerangka tektonik yang membentuk kepulauan Indonesia juga menjadikan wilayah ini kaya akan sumberdaya geologi. Tumbukan antar-lempeng sejak era geologi jutaan tahun silam telah memicu aktivitas magmatis yang menghasilkan mineral ekonomi melimpah, seperti timah, tembaga, perak, dan emas. Bahkan, 40% potensi sumber energi panas bumi dunia ada di Indonesia.
Kegiatan vulkanisme ini juga menimbulkan munculnya untaian gunung berapi berjajar menghiasi setiap pulau, menjulang ratusan bahkan ribuan meter di atas muka air laut. Hal ini memberikan lansekap sangat indah dan lingkungan yang segar. Kombinasi antara endapan vulkanik yang kaya unsur hara dan curah hujan yang tinggi telah memberikan kondisi tanah yang sangat subur.
Namun, di sisi lain, keindahan dan kesuburan ini juga menyimpan potensi ancaman bencana yang sangat beragam. Hampir segala macam bencana dapat dijumpai di Indonesia, dan dilihat dari kerawanannya, Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami dan erupsi gunung api.
Meski secara intensitas, bencana alam di Indonesia tidak setinggi bencana hidrometeorologi, seperti, banjir, longsor dan angin puting beliung– yang hampir mencapai 80%, namun potensi kerugian yang ditimbulkan bencana alam cenderung lebih besar.
Kondisi tersebut disebabkan karena masyarakat lebih familiar bencana hidrometeorologi, sehingga secara tidak langsung akan tergerak untuk menyiapkan diri dalam menghadapi bencana tersebut.
Maka, yang jadi pertanyaan adalah, seberapa besar sebetulnya kapasitas masyarakat kita dalam upaya mengurangi risiko bencana?
Kapasitas, secara definisi berarti, kemampuan masyarakat ataupun daerah untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman, risiko dan potensi kerugian akibat bencana, secara terstruktur, terencana dan terpadu.
Peningkatan kapasitas masyarakat bisa dilakukan melalui proses sosialisasi, edukasi dan pembelajaran akan strategi penanggulangan bencana, baik kepada masyarakat umum atau kepada kelompok rentan, seperti, kalangan perempuan, kelompok usia dini dan kalangan disabilitas.
Upaya peningkatan kapasitas masyarakat juga bisa dilakukan berbasis komunitas. Seperti, komunitas masyarakat pedesaan, pelajar, santri dan lain sebagainya.

Berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah kejadian bencana di Indonesia periode 1 Januari-30 Mei 2024 telah mencapai 840 kejadian.
Kejadian bencana alam yang mendominasi adalah bencana hidrometeorologi sebanyak 98,81 persen. Sisanya, bencana geologi sebesar 1,19 persen, dengan urutan; bencana banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor dan gempa bumi.
Dari jumlah kejadian itu, dampak yang ditimbulkan mengakibatkan korban meninggal sebanyak 260 orang, korban hilang 26 orang, dan korban yang mengalami luka-luka sebanyak 407 orang.
(sumber: https://bnpb.go.id/ )
Mengingat masih tingginya jumlah korban bencana dalam kurun 5 bulan ini, maka sudah selayaknya jika pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota mengubah paradigma penanganan bencana dari penanganan responsif saat tanggap darurat menjadi preventif saat pencegahan dan kesiapsiagaan.
Untuk itu, maka ada beberapa upaya peningkatan kapasitas yang perlu dikuatkan dalam rangka pengurangan risiko bencana.
Pertama, perlu dilakukan pencanangan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga, khususnya di tingkat pemerintahan yang paling rendah, yaitu desa/kelurahan. Bahkan, jika memungkinkan rencana penanggulangan bencana (RPB) harus dimasukkan dalam RPJM Desa, dan Pemerintah Desa juga perlu mengalokasikan anggaran dana desa untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Kedua, perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi tentang desa tangguh bencana guna pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana, baik melalui publikasi leaflet yang ditempel di tempat-tempat strategis atau melalui media informasi lainnya.
Ketiga, perlu juga dihadirkan ide-ide kreatif dalam menyampaikan materi sosialisasi dan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan perangkat desa, guna memancing rasa keingintahuan masyarakat terhadap RPB.
Keempat, dalam upaya penanggulangan bencana, perlu pelibatan berbagai elemen masyarakat, yang disebut dengan unsur penthahelix. Yakni, pemerintah, masyarakat, kelompok akademisi, kalangan dunia usaha dan media massa.
Pelibatan unsur penthahelix ini sangat penting karena bencana adalah urusan bersama, yang penanggulangannya tidak cukup hanya ditangani pemerintah saja. (*)
*Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unair Surabaya